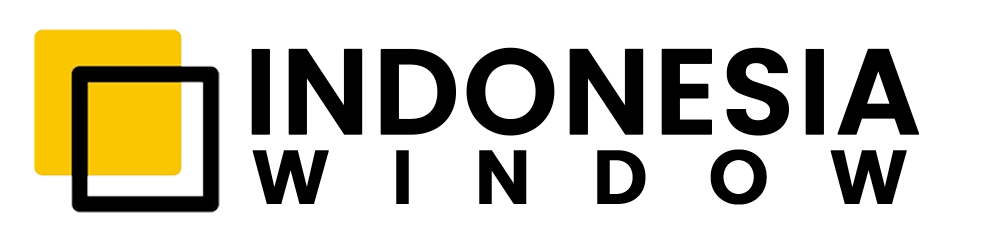Oleh Achmad Ubaedillah [Dosen FISIP Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta]Radikalisme dan terorisme merupakan persoalan yang hingga kini masih dihadapi oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Beberapa catatan historis menunjukkan bahwa kawasan ini merupakan ‘ladang subur’ bagi berkecambahnya berbagai kelompok radikal dan teroris.
Kenyataan ini terjadi jauh sebelum terjadinya
tragedi 9/11 dan propaganda Global War on Terrorism (GWoT) yang dikumandangkan oleh Presiden Amerika Serikat George Walker Bush.
Seiring waktu, kelompok radikal dan teroris di kawasan Asia Tenggara mengalami metamorfosis yang signifikan, terutama di dalam pengembangan jaringan, keahlian serta sumber daya yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menjadi ancaman potensial bagi stabilitas keamanan dan politik di tingkat negara dan kawasan.
Keamanan negara dan kawasan yang terganggu dapat berimplikasi negatif terhadap sektor lainnya seperti perokonomian dan pariwisata.
Tulisan ini akan mencoba mengulas secara singkat mengenai radikalisme dan terorisme di Asia Tenggara serta potensi ancaman terhadap keamanan di tingkat kawasan dengan menggunakan kerangka konseptual Ilmu Sosial, khususnya Studi Hubungan Internasional tentang konsep Ancaman (Threat) dan Keamanan Internasional (International Security).
Di samping itu, tulisan ini juga akan menyoroti beberapa kasus radikalisme dan terorisme yang terjadi di beberapa negara ASEAN yakni Filipina, Thailand, dan Indonesia.
Genealogi radikalisme dan terorismePerbincangan mengenai radikalisme dan terorisme tidak dapat dilepaskan dari perdebatan dirskusus teoretik-akademik yang melingkupinya. Hingga tulisan ini dibuat
belum terdapat kesepakatan yang bulat di kalangan pakar Ilmu Sosial mengenai definisi dari radikalisme dan terorisme.
Namun dari berbagai pendapat yang bermunculan terdapat titik persamaan, yakni penggunaan kekerasan di dalam cara mencapai suatu tujuan. Radikalisme secara etimologi berasal dari kata bahasa Yunani, yakni Radix yang berarti akar, sehingga radikal mempunyai arti cara berpikir yang mengakar, mendalam, komprehensif dan holistik.
Radikalisme dalam kajian Ilmu Sosial didefinisikan sebagai sebuah pandangan yang ingin melakukan perubahan radikal sesuai dengan ideologi yang diyakininya atau tafsirannya atas realitas sosial (Hasani, 2010). Pengertian lain terkait radikalisme yakni suatu pemahaman yang ingin mewujudkan perubahan secara cepat dengan menggunakan cara-cara kekerasan.
Dalam praktiknya radikalisme seringkali digandengkan dengan kata agama, sehingga tercipta terminologi lainnya, yakni radikalisme agama yang dapat definisikan sebagai sikap dan perilaku seseorang atau kelompok yang menerapkan cara-cara kekerasan dengan menggunakan agama sebagai instrumen politis dalam mencapai tujuannya.
Penganut radikalisme agama acapkali mendasari sikap dan perilakunya pada tafsiran kaku atas sumber-sumber doktrinal agama tanpa mempertimbangkan aspek konteks dan kajian multidisipliner (Idris, 2017).
Radikalisme seringkali menjadi titik masuk bagi terbentuknya terorisme. Sementara itu, terorisme dapat didefinisikan sebagai segala tindakan yang membenarkan penggunaan kekerasan fisik secara masif guna menggapai suatu tujuan, menciptakan teror dan rasa takut terhadap lawan politik serta lingkungan sosial di sekitarnya agar tunduk dan tidak berdaya (Hasani, 2010).
Terorisme merupakan sebuah instrumen dari suatu proyek politik dan agama dimana para pelakunya seringkali menjalankan aksi-aksi kekerasan secara demonstratif demi meraih dukungan. Tidak hanya itu, aksi-aksi kekerasan tersebut biasanya berupa ancaman dalam rangka mengintimidasi dan menyudutkan pihak yang ditargetkan (Schmid, 2011).
Menurut
General Assembly Resolution 49/60 of 9 December 1994, secara khusus
terorisme didefinisikan sebagai suatu tindakan pidana yang dilakukan guna memprovokasi dan meneror khalayak umum. Tindakan tersebut dilakukan oleh orang tertentu maupun sekelompok orang untuk mencapai tujuan politik tertentu dengan didasari oleh alasan politis, filosofis, ideologis, ras, etnis, dan agama guna menjustifikasi tindakan mereka (http://www.undocuments.net/a49r60.htm).
Fenomena radikalisme dan terorisme bukan merupakan sesuatu yang muncul dari kevakuman tanpa sebab. Sebuah studi menjelaskan, setidaknya terdapat lima faktor pemicu terbentuknya radikalisme dan terorisme, yakni: pertama, faktor psikologis (abnormalitas kejiwaan); kedua, faktor sosiologis (tingkat pendidikan, pergaulan).
Ketiga, faktor ekonomi (kemiskinan, pengangguran); keempat, faktor politik (penolakan terhadap demokrasi dan HAM); dan kelima, faktor agama (fanatisme, skriptualisme, dogmatisme).
Dalam kenyataan di lapangan, acapkali ditemukan fakta bahwa fenomena radikalisme dan terorisme tidak hanya disebabkan oleh faktor pemicu tunggal, melainkan oleh kombinasi faktor pemicu (Esposito, 2007, Veldhuis, 2009).
Di sisi lain, terdapat pendapat yang meyakini bahwa radikalisme dan terorisme secara dominan disebabkan oleh faktor politik, sedangkan faktor-faktor lain berperan sebagai katalisator (Azra, 2015).
Penyebaran radikalisme dan terorisme sangat ‘contagious’. Seseorang atau kelompok yang terjangkiti radikalisme dan terorisme dengan mudah dapat menularkannya ke orang atau kelompok lain (Azra, 2020).
Dari catatan historis yang ditemukan, dalam konteks internasional, istilah terorisme sebenarnya telah digunakan dan diperkenalkan oleh Liga Bangsa-bangsa (LBB), kemudian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada 1937 saat penyelenggaraan Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism (Marston, 2003).
Namun, persoalan terorisme kembali menyeruak ke permukaan ketika terjadi peristiwa ‘9/11 Attacks’di Amerika Serikat yang berhasil menggemparkan publik internasional serta berimplikasi pada konstelasi hubungan internasional kala itu.
Tragedi ‘9/11 Attacks’ yang oleh sebagian pihak dikenal sebagai ‘Black Tuesday’ telah membuat otoritas Negeri Paman Sam di bawah kepemimpinan Presiden George Walker Bush meluncurkan kebijakan strategis, yakni Global War on Terror (GWoT) yang mendapat beragam respon di berbagai kawasan, terutama Dunia Islam.
Semenjak itu radikalisme dan terorisme menjadi diskursus kritis dan isu global yang diperbincangkan oleh banyak pihak, mulai cendekiawan hingga para pembuat kebijakan (decision makers) di berbagai negara (Winarno, 2014).
Dalam konteks Studi Hubungan Internasional, beberapa pengkaji mencoba mengaitkan konsep seperti persepsi ancaman (threat perception) dan keamanan internasional (international security) dengan radikalisme dan terorisme sebagai fenomena dan isu kontemporer (Collins, 2003, Emmers & Sebastian, 2005). Hal demikian juga akan diketengahkan dalam tulisan di bawah ini.
Konseptualisasi persepsi ancaman dan keamanan internasionalPerbincangan mengenai persepsi ancaman (threat perception) tidak dapat dilepaskan dari cara pandang aktor dalam mengindentifikasi objek dan fenomena yang membahayakan dirinya. Kehadiran hal yang membahayakan dirinya tersebut kemudian dianggap sebagai ancaman.
Dengan terbentuknya persespi ancaman tadi, kemudian aktor memformulasikan dan mengaplikasikan seperangkat aturan maupun kebijakan sebagai upaya dalam mencegah, menghindari, membalas maupun memberhentikan ancaman yang datang (Muhibat, 2013).
Sementara itu, konsep persepsi ancaman yang lebih
reliable, mendefinisikan persepsi ancaman sebagai situasi dan kondisi ketika aktor, baik individu maupun kelompok memiliki kapabilitas dan intensi guna menimbulkan konsekuensi negatif bagi aktor lain (Davis, 2003).
Terdapat dua kategori ancaman, yakni ancaman terhadap aktor dan ancaman terhadap kumpulan aktor. Kemudian, bentuk ancaman terhadap kumpulan aktor dapat berupa ancaman militer, ancaman ekonomi dan ancaman sosial-budaya (Rosseau, 2007).
Persepsi ancaman bersifat dinamis. Maksudnya relatif dipengaruhi perubahan pada cara pandang aktor dalam memandang realitas. Dalam kadar dan keadaan tertentu, persepsi ancaman turut memberikan dampak terhadap pembentukan kepentingan nasional (national interest), arah kebijakan luar negeri, dan keamanan di tingkat regional serta internasional.
Perdebatan besar ke-1 (The First Great Debate) dalam Studi Hubungan Internasional antara Liberalisme dengan Realisme tidak dapat dipisahkan dari problem keamanan. Salah satunya terkait dengan pertanyaan mendasar “Bagaimana suatu negara dapat menghindari terjadinya perang?”. Atas dasar itu, diskursus keamanan yang berlangsung pada masa kini sangat bersifat militeristik dan state-centric (Baylis, 2020).
Seiring waktu, keruntuhan Uni Soviet/Blok Timur secara resmi mengakhiri Perang Dingin. Dunia internasional kemudian memasuki pembabakan sejarah baru, yakni periode pasca perang dingin yang dicirikan dengan tampilnya multipolaritas dalam kancah internasional.
Disamping itu, kompleksitas dan mutlidimensionalitas persoalan internasional menjadi kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Dua prakondisi tersebut telah berdampak signifikan terhadap terjadinya evolusi makna keamanan (Buzan 1991, Winarno 2014).
Konsep keamanan pada masa perang dingin yang biasa dikenal sebagai keamanan tradisional (traditionalsecurity) mengalami evolusi makna dan redefinisi, sehingga belakangan memunculkan konsep baru yang disebut keamanan non-tradisional (non-traditional security).
Dalam tataran teoretis, keamanan non tradisional dapat dipahami sebagai sebuah konsepsi keamanan yang hirau terhadap individu, kelompok, maupun milieu (lingkungan). Titik perhatian terhadap keamanan individu selanjutnya menjadi stimulus bagi institusi global semisal UNDP untuk menuangkannya ke dalam sebuah konsep yang disebut keamanan manusia (human security).
Terdapat lima dimensi keamanan yaitu; pertama, keamanan militer (military security), melingkupi persepsi militer atas intensi yang hadir serta kemampuan dalam hal defensif dan ofensif ; kedua, keamanan politik (political security), melingkupi ideologi, stabilitas dan keberlanjutan suatu negara.
Ketiga, keamanan ekonomi (economic security), meliputi akses terhadap sumber daya, pasar dan finansial yang merupakan penopang kesejahteraan negara; keempat, keamanan sosial (societal security), melingkupi pola tradisional semisal kultur, identitas nasional dan agama; kelima, keamanan lingkungan (environmental security), terkait keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan hidup sebagai lokus dimana manusia itu hidup (Buzzan, 1991).
Merujuk Buzan, pemikir utama ‘The Copenhagen School’, keamanan non-tradisional tidak hanya hirau pada isu high politics layaknya persoalan militer, tetapi juga isu low politics seperti persoalan lingkungan hidup, kesetaraan
gender, kejahatan transnasional, radikalisme dan terorisme.
Disamping itu, keamanan non-tradisional juga memberikan ruang artikulasi bagi keterlibatan aktor non negara (non-state actors) misalnya pihak swasta, lembaga masyarakat sipil, organisasi keagamaan dan sejenisnya (Buzan & Hansen, 2009).
Sejauh ini, persoalan keamanan menempati posisi sentral dalam khazanah intelektual Hubungan Internasional, setidaknya dapat dibuktikan dengan tingginya atensi dan minat pengkaji yang datang dari berbagai disiplin keilmuan dalam meneliti keamanan.
Dengan merujuk pada paparan di atas, negara-negara di kawasan Asia Tenggara - ASEAN - secara umum selama ini didapati telah mempersepsikan fenomena radikalisme dan terorisme sebagai salah satu ancaman bagi pemeliharaan dan keberlangsungan keamanannya.
Di samping itu, ancaman radikalisme dan terorisme juga turut berdampak pada berbagai dimensi keamanan yang meliputi militer, politik, ekonomi, sosial serta lingkungan. Praktik di beberapa negara Asia Tenggara menunjukkan, ancaman radikalisme dan terorisme dalam batas tertentu juga turut berimplikasi terhadap perubahan arah kebijakan luar negeri suatu negara.
Beberapa Studi Kasus: Filipina, Thailand, dan Indonesia ‘bara api dalam sekam’ menjadi ungkapan yang kompatibel dalam mendeskripsikan fenomena radikalisme dan terorisme yang terjadi di kawasan Asia Tenggara.
Ungkapan ‘bara api’ dapat diasosiasikan dengan gerakan radikalisme dan terorisme yang sewaktu-waktu dapat membakar ‘sekam’ kawasan Asia Tenggara. Berbagai gerakan radikalisme dan terorisme, baik yang berdimensi agama maupun tidak, ditengarai oleh banyak pihak telah lama eksis jauh sebelum tragedi ‘9/11 Attacks’ di Amerika Serikat yang menggemparkan publik internasional.
Di bawah ini akan disinggung secara singkat kasus-kasus radikalisme dan terorisme di kawasan Asia Tenggara yang terjadi di beberapa negara seperti Filipina, Thailand, dan Indonesia.
Sejak 1994, Moro Islamic Liberation Front (MILF) telah menampakan eksistensinya di Filipina Selatan. Secara umum, MILF merupakah organisasi revolusioner yang teguh berjuang bagi Muslim Filipina Moro guna mencapai cita-cita untuk dapat menentukan nasib sendiri (self-determination).
Catatan historis menunjukkan bahwa kelompok minoritas Muslim Moro telah lama mengalami perlakuan diskriminatif hingga stigmatisasi sebagai orang ‘Moor’ yang berarti buta huruf, tidak bertuhan, jahat dan gemar membunuh (Lubis, 2018).
MILF memiliki struktur dan basis komando kuat yang tersebar di beberapa wilayah, yakni Maguindanao, Basilian, Cotabago, Lanao Del Sur, Zamboanga Del Norte, Bukindon Agusa, Sulatan Kudarat, dan Sarangani. Suatu data menunjukkan bahwa MILF didukung oleh sekitar 12000 militan pada masing-masing wilayah tersebut (Chalk, 2009).
Selain itu terdapat pula organisasi Abu Sayyaf Group (ASG) yang mempunyai tujuan menegakkan syariat Islam di Filipina. ASG acapkali menggunakan cara-cara kekerasan dalam mencapai tujuannya.
Oleh sebagian pengkaji radikalisme dan terorisme, ASG dikategorikan sebagai organisasi radikal teror yang berbahaya bagi stabilitas keamanan nasional Filipina dan keamanan regional Asia Tenggara (Chalk, 2009).
Di samping itu, ASG ditopang oleh sekitar 300-500 militan yang mempunyai basis kuat di wilayah Maguindanao. Implikasi sepak terjang ASG terhadap ancaman keamanan di kawasan salah satunya dapat dibuktikan dalam maraknya kasus penyanderaan terhadap warga negara asing (WNA) yang tidak jarang mengganggu hubungan bilateral antarnegara.
Semisal Indonesia, sejak 2016 didapati data bahwa sebanyak 44 Warga Negara Indonesia (WNI) pernah menjadi korban sandera kelompok ASG (Kompas, 2021). Sementara itu, di Thailand terdapat kelompok Melayu Muslim Pattani yang hingga kini masih eksis dalam mempengaruhi dinamika sosial-politik Negeri Gajah Putih.
Setidaknya terdapat tiga faktor pemicu kemunculan gerakan radikal Melayu Muslim Pattani di Thailand Selatan yakni: pertama, fakta historis berupa penggabungan wilayah Kesultanan Pattani oleh Kerajaan Inggris ke dalam Kerajaan Siam melalui Anglo-Siam Treaty.
Kedua, kebijakan asimilasi paksa yang dicanangkan pemerintah kerajaan, dan ketiga; ketidakadilan yang mengakibatkan ketimpangan ekonomi dan keterpurukan kehidupan sosial masyarakat Melayu Muslim Pattani.
Ketidakadilan dan kenestapaan panjang yang dialami oleh kelompok Melayu Muslim Pattani membuat kekuatan mereka semakin terkonsolidasi melalui pembentukan berbagai sayap organisasi seperti Barisan Revolusi Nasional (BRN), Gerakan Mujahidin Islam Pattani (GMP) dan Pattani United Liberation Organization (PULO).
Selain itu, kelompok Melayu Muslim Pattani juga didukung dengan kelengkapan persenjataan yang memadai seperti senjata api, M 16, AK 47 Assault Riffles,
shotguns, granat dan bom rakitan. Basis terbesar kelompok Melayu Muslim Pattani terdapat di wilayah Yala dan Narathiwat, dimana sekitar 90 persen penduduk disana merupakan pendukungnya (Kingsbury, 2005).
Di Indonesia, keruntuhan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto telah berimplikasi secara langsung terhadap keterbukaan ruang publik bagi masyarakat sipil seperti organisasi masyarakat (Ormas).
Sejak saat itu, lahir sejumlah kelompok dan ormas berbasis keagamaan (Islam) yang ditengarai mendukung gerakan radikalisme dan terorisme seperti Jama’ah Islamiyah (JI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Laskar Jihad, Laskar Mujahidin, Laskar Jundullah, Ring of Banten dan sebagainya (Hilmy, 2015).
JI sendiri merupakan organisasi radikal dan jaringan terorisme terbesar di kawasan Asia Tenggara yang bergerak secara kladenstin. JI disinyalir memiliki keterkaitan erat dengan jaringan dan aktivisme teroris di Timur Tengah, khususnya Al-Qaeda.
Metamorfosis gerakan JI menjadi perhatian serius dari berbagai negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Filipina dan Singapura. Sementara itu, kekhawatiran publik Indonesia dan dunia internasional semakin tertuju kepada JI sejak terjadinya rentetan aksi peledakan bom.
JI diperkirakan memiliki ribuan anggota aktif dan sekitar 200 di antaranya telah mengalami penyelidikan di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Filipina. Tujuan JI adalah merebut dan ‘menaklukkan’ wilayah-wilayah yang telah dihuni oleh masyarakat sebagai target operasi serta mewujudkan tatanan pemerintahan yang berlandaskan hukum Islam (Syariah) di kawasan Asia Tenggara (Winarno, 2014)
Perlu kajian lebih lanjutRadikalisme dan terorisme merupakan permasalahan laten di Kawasan Asia Tenggara yang akan terus menarik untuk dikaji. Kerangka konseptual Hubungan Internasional berupa persepsi ancaman (threat perception) dan keamanan internasional (international security) dalam paparan di atas menunjukkan bahwa permasalahan radikalisme dan terorisme masih menjadi ancaman yang potensial bagi stabilitas keamanan di kawasan yang dapat berimplikasi secara langsung maupun tidak langsung terhadap sektor penting lainnya seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya.
Sementara itu, multitrack diplomacy berupa dialog dan kerja sama antara institusi agama dan masyarakat sipil (civil society) perlu diwujudkan dalam rangka memperkuat langkah dan upaya pemerintah negara-negara ASEAN dalam mencegah dan menanggulangi radikalisme dan terorisme di kawasan Asia Tenggara. Akhirnya, tulisan ini masih membutuhkan kajian lebih lanjut guna mendapatkan hasil yang lebih memadai dan komperhensif.
Selesai