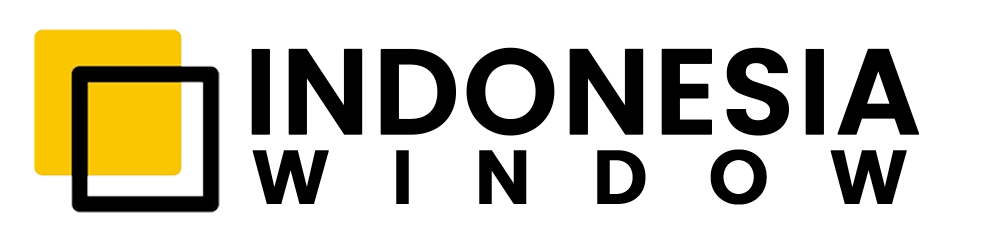Feature – Menyusuri jejak masa lalu di Pecinan Glodok, dari klenteng, gereja, hingga tradisi teh China

Foto yang diabadikan pada 24 Januari 2026 ini menunjukkan gapura pecinan kawasan Pancoran Glodok yang terletak di Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat. (Xinhua/Noviyanti)
Jakarta (Xinhua/Indonesia Window) – Kawasan Pecinan Glodok bukan sekadar pusat perdagangan atau destinasi wisata kuliner, melainkan ruang hidup yang menyimpan sejarah panjang, ingatan kolektif, serta dinamika budaya masyarakat Tionghoa peranakan di Jakarta. Jelang Imlek tahun ini, Xinhua berkesempatan menelusuri jejak-jejak masa lalu itu bersama Elsa Novia Sena, seorang kreator konten Tionghoa peranakan yang aktif mengangkat sejarah dan budaya Tionghoa peranakan.
Baru-baru ini, kami menyusuri sudut-sudut Glodok sambil mengurai kisah tentang asal-usul kawasan, praktik keagamaan, hingga tradisi yang masih bertahan di tengah perubahan zaman.
Asal muasal Pecinan Glodok
Perjalanan dimulai dari gapura Pecinan Glodok, sebuah bangunan yang relatif baru tetapi sarat simbol. Gapura tersebut diresmikan pada tahun 2022 dan dibangun melalui inisiatif pihak swasta sebagai penanda kawasan bersejarah. Di balik wujudnya yang kokoh dan modern, kawasan yang dilaluinya justru menyimpan cerita jauh lebih tua. Salah satunya adalah asal-usul nama Glodok, yang kerap dikaitkan dengan sebutan ‘Pancoran Glodok’.
Elsa menuturkan bahwa menurut versi yang paling banyak dikenal, nama ini berasal dari pancuran air yang terbuat dari kayu. Saat air mengalir dan jatuh, pancuran tersebut menimbulkan bunyi khas "grojok, grojok". Pelafalan masyarakat Tionghoa pendatang pada masa awal, yang terdengar cadel, mengubah bunyi tersebut menjadi "gelodok". Dari sanalah nama Glodok kemudian melekat dan bertahan hingga kini, meskipun terdapat pula versi-versi lain dalam cerita lisan masyarakat.
Kawasan Pecinan Glodok tidak dapat dilepaskan dari peristiwa sejarah besar yang membentuknya, yakni Geger Pecinan tahun 1740. Peristiwa ini merupakan salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah Batavia, ketika ribuan warga etnis Tionghoa dibantai oleh pemerintah kolonial Belanda. Perkiraan jumlah korban mencapai lebih dari 10.000 jiwa. Tragedi tersebut menjadi titik balik yang menyebabkan komunitas Tionghoa kemudian dipusatkan di kawasan di luar tembok Kota Batavia, yang kelak berkembang menjadi Pecinan Glodok.
Wihara Dharma Sakti
Dari gapura, kami menyusuri destinasi berikutnya yaitu Kompleks Kelenteng Djin De Yuan, yang juga dikenal sebagai Wihara Dharma Sakti. Kelenteng ini merupakan salah satu yang tertua di Jakarta, didirikan sekitar pertengahan abad ke-17. Sebelumnya, tempat ibadah ini dikenal dengan nama Kwan Im Teng, yang berarti tempat pemujaan Dewi Kwan Im.
Bangunan ini sempat mengalami kebakaran hebat pada 2015 dan hingga kini masih dalam proses pemulihan, tetapi fungsinya sebagai pusat spiritual dan budaya etnis Tionghoa di Glodok tetap berjalan.
Masih di dalam kompleks yang sama, kami juga menyambangi Kelenteng Tee Tjang Wang, yang dikenal sebagai tempat sembahyang leluhur dan penghormatan terhadap arwah. Pada waktu-waktu tertentu, seperti perayaan Imlek, Ceng Beng, dan Bulan Hantu, kelenteng ini dipadati umat yang datang untuk berdoa. Tradisi penghormatan kepada leluhur diwujudkan melalui rangkaian doa serta pembakaran kertas persembahan, seperti uang dan perlengkapan simbolis, yang dilakukan di area khusus demi keamanan lingkungan sekitar.
Menariknya, kelenteng ini juga memiliki altar penghormatan bagi tokoh yang dianggap berjasa dan memiliki keteladanan moral. Dalam tradisi kepercayaan Tionghoa, figur tersebut kerap berasal dari manusia biasa yang kemudian dihormati setelah wafat, sebagai wujud ingatan kolektif dan penghargaan atas nilai-nilai kebajikan yang mereka wariskan.
"Konsep dewa-dewi Tionghoa itu sejarah asalnya adalah manusia yang berjasa bagi masyarakat dan setelah meninggal dihormati oleh masyarakat. Jadi, kegiatan berdoa kepada dewa-dewi ini bukan berarti menyembah, tetapi lebih kepada pengungkapan rasa terima kasih atas jasa mereka," kata Elsa.
Gereja Santa Maria de Fatima
Jejak sejarah lintas iman terlihat jelas ketika menyambangi Gereja Katolik Santa Maria de Fatima. Bangunan ini pada awalnya merupakan rumah seorang kapitan Tionghoa, yakni pemimpin komunitas Tionghoa yang diangkat oleh pemerintah kolonial Belanda. Rumah tersebut diperkirakan telah berdiri sejak pertengahan abad ke-19 dan memiliki arsitektur khas dengan atap melengkung, berbeda dari rumah tinggal pada umumnya.
Pada paruh kedua abad ke-20, bangunan ini beralih fungsi menjadi gereja Katolik. Meskipun telah ditambahkan simbol salib, bentuk arsitekturnya yang menyerupai kelenteng kerap membuat orang keliru mengira bangunan ini sebagai tempat ibadah tradisional Tionghoa.
Di gereja ini pula, peserta diperkenalkan dengan filosofi simbol-simbol tradisional, termasuk sepasang singa batu yang diletakkan di bagian depan. Singa jantan digambarkan memegang bola dunia sebagai simbol kepemimpinan dan kekuatan, sementara singa betina memegang anak sebagai lambang kelahiran dan perawatan. Penempatan keduanya mencerminkan keseimbangan Yin dan Yang, filosofi yang juga diterapkan dalam tradisi pernikahan hingga pemakaman masyarakat Tionghoa.
"Posisi sepasang singa batu ini tidak pernah berubah, jantan di kiri dan betina di kanan dari arah depan. Hal ini selaras dengan konsep Yin dan Yang di mana perempuan dilambangkan sebagai energi lemah (Yin) dan laki-laki dilambangkan sebagai energi kuat (Yang), bagi mereka yang masih mengikuti kepercayaan Tionghoa, ketika ada pasangan yang melangsungkan sangjit (lamaran) atau pernikahan, posisi perempuan berada di kanan dan laki-laki di kiri, sama halnya dengan makam Tionghoa yang biasanya berukuran besar, karena dalam satu liang untuk sepasang suami istri, posisi suami berada di sebelah kiri dan istri di sebelah kanan. Salam dalam tradisi Tionghoa menempatkan posisi tangan kiri di atas tangan kanan, hal ini memiliki makna filosofis dalam ajaran Konghucu yakni yang kuat melindungi yang lemah," papar Elsa.
Kelenteng Toasebio
Perjalanan berlanjut ke Kelenteng Toasebio, salah satu kelenteng tua di Glodok yang telah berdiri sebelum 1740 dan sempat dibangun kembali pada 1751 setelah mengalami kebakaran. Kelenteng ini kini berstatus sebagai bangunan cagar budaya dan dilengkapi papan informasi sejarah. Pada hari-hari tertentu, khususnya tanggal 1 dan 15 dalam penanggalan Imlek, kelenteng ini dipadati umat yang datang untuk bersembahyang.
Dewa utama di Kelenteng Toasebio dikenal sebagai Cheng Goan Cheng Kun, yang dalam tradisi Tionghoa kerap dikaitkan dengan figur Dewa Erlang beserta ikon anjing langitnya. Di dalam kompleks kelenteng, terdapat pembagian ruang ibadah yang mengikuti aturan tertentu. Bahkan, di bagian belakang terdapat area wihara yang digunakan khusus oleh penganut Buddha.
Kelenteng Tan Seng Ong
Langkah kami berlanjut ke Kelenteng Tan Seng Ong, sebuah kelenteng marga yang awalnya dibangun oleh keluarga bermarga Tan sekitar abad ke-18. Kelenteng ini berfungsi sebagai tempat perlindungan dan pemujaan dewa pelindung marga, sebelum akhirnya dibuka untuk umum.
Elsa menceritakan bahwa "Dahulu, Tan Seng Ong merupakan seorang prajurit yang berhasil melindungi wilayahnya. Jadi, orang-orang bermarga Tan merantau dan membawa patung tokoh tersebut ke daerah ini untuk melindungi mereka, sebagai simbol dewa pelindung."
Bangunan ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya dan dikenal karena arsitektur kayunya yang khas. Kayu jati gelondongan digunakan sebagai penyangga utama, sementara ukiran tiga dimensi buatan tangan menghiasi hampir seluruh bagian bangunan.
Tata ruang terbuka, kolam ikan, serta ventilasi alaminya tidak hanya mencerminkan prinsip Feng Shui, tetapi juga menciptakan suasana sejuk di dalam kelenteng. Namun, perawatan bangunan bersejarah semacam ini memerlukan biaya yang sangat besar, sehingga pengelolaannya sangat bergantung pada yayasan yang menaunginya.
Tradisi seduh teh China
Sebagai penutup, kami singgah di kedai Pieces of Peace di kawasan Petak Enam guna merasakan pengalaman Gong Fu Cha atau seni tradisional menyeduh teh asal China yang menekankan ketelitian, kebersihan, dan penghormatan kepada tamu.
Kami berkesempatan mencicipi teh hijau Biluochun dan teh putih Silver Needle, sambil mempelajari suhu air yang tepat, urutan penyeduhan, hingga etika minum teh. Tradisi ini tidak sekadar menjadi praktik kuliner, tetapi juga sarana untuk menanamkan nilai kesabaran, penghormatan, dan kesadaran dalam interaksi sosial.
Singkat cerita, perjalanan ini menjadi upaya merawat ingatan kota, menghubungkan masa lalu dengan masa kini, serta mengingatkan bahwa sejarah Jakarta dibentuk oleh keberagaman budaya, keyakinan, dan tradisi yang saling berdampingan. Di tengah arus modernisasi, Glodok tetap berdiri sebagai ruang hidup yang menyimpan cerita, luka, dan warisan yang layak untuk terus diingat dan dipahami.
Laporan: Redaksi
Bagikan
Komentar
Berita Terkait

Ilmuwan peringatkan kaitan ‘long COVID’ dengan bunuh diri
Indonesia
•
09 Sep 2022

AL WAFI PEDULI PALESTINA
Indonesia
•
03 Nov 2023

Ratu bulu tangkis Taiwan itu juga seorang doktor
Indonesia
•
29 May 2021

Ledakan di pelabuhan Iran tewaskan 25 orang, 800 terluka
Indonesia
•
27 Apr 2025
Berita Terbaru

Berita buatan AI makin mendominasi, ‘think tank’ Inggris desak pemerintah susun aturan
Indonesia
•
02 Feb 2026

Belanda selidiki Roblox karena potensi risiko bagi anak di bawah umur
Indonesia
•
31 Jan 2026

Flu landa AS, 20 juta kasus ditemukan pada musim flu saat ini, belasan ribu tewas
Indonesia
•
31 Jan 2026

Waspada! 2 kasus virus Nipah dilaporkan di India
Indonesia
•
31 Jan 2026