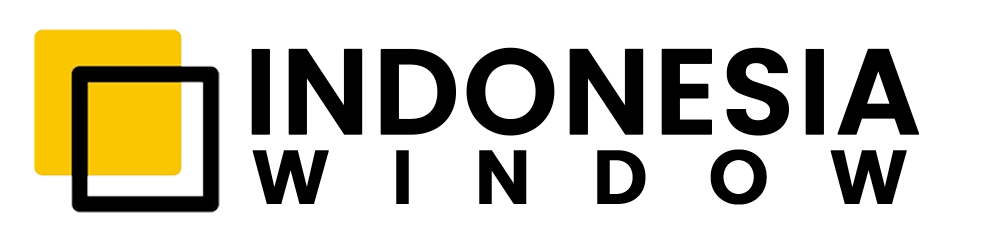Jakarta (Indonesia Window) - Seorang keponakan di Bondowoso ingin masuk Sekolah Menengah Atas (SMA) favorit di Jember, Jawa Timur. Apa lacur, meski nilainya memenuhi syarat, dirinya tidak diperbolehkan masuk ke SMA Negeri 2 Jember karena tinggal di luar zona sekolah itu. Walhasil, dia terpaksa memilih SMA lokal.
Kabar dirinya yang “digagalkan” masuk sekolah impiannya karena terbentur sistem zonasi akhirnya sampai ke Inggris di mana saya saat ini menetap.
Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, sistem zonasi merupakan bentuk penyesuaian kebijakan dari sistem rayonisasi. Rayonisasi lebih memperhatikan pada capaian siswa di bidang akademik, sementara sistem zonasi lebih menekankan pada jarak atau radius antara rumah siswa dan sekolah. Dengan demikian, maka siapa yang lebih dekat dengan suatu sekolah lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah itu.
Sistem ini sebenarnya tak jauh berbeda dari sistem pendidikan di Inggris.
Zonasi di InggrisDi negeri Big Bang ini, sistem zonasi sudah lama diterapkan untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga SMA yang dikenal dengan istilah “catchment area”. Sistem ini diberlakukan bagi “state school” (sekolah yang dibiayai oleh negara), namun tidak bagi “private school” atau sekolah swasta.
Sekolah swasta di Inggris (dan mungkin di manapun di dunia) berhak menentukan siapa yang akan menjadi siswa mereka. Untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), calon siswa biasanya harus mengikuti tes masuk dan wawancara. Sedangkan untuk tingkat SD, sebagian proses penerimaan siswa mengacu pada informasi yang diberikan dalam surat atau formulir permohonan (school application).
Guna memastikan suatu "state school" berkualitas, pemerintah melalui "Office for Standards in Education, Children's Services and Skills" (OFSTED) atau Kantor Urusan Standar Pendidikan, Pelayanan Anak dan Keahlian melakukan penilaian pada seluruh sekolah.
OFSTED melakukan inspeksi ke sekolah dan menilai berbagai fasilitas yang disediakan bagi para siswa. Inspeksi kadang dilakukan dadakan dan ada kalanya terencana.
Mereka akan menilai bagaimana sekolah mendukung proses belajar siswa. Apakah sekolah mampu membuat siswa berkembang, mengembangkan potensi besar mereka, mengadopsi nilai-nilai ideologi dasar, serta kualitas pengajaran di sekolah tersebut.
Setelah itu OFSTED akan membuat laporan yang bisa diakses oleh masyarakat lewat internet. Jadi setiap orang bisa membaca hasil laporan tersebut secara lengkap, dan mengetahui apakah suatu sekolah memiliki tingkat Grade 1: outstanding (sangat bagus); Grade 2: good (bagus); Grade 3: requires improvement (perlu peningkatan); atau Grade 4: inadequate (kurang bagus).
KemauanSetiap orangtua di Inggris tentu ingin anaknya masuk sekolah “outstanding”.
Tak heran kalau biasanya orangtua mati-matian pindah ke rumah yang masuk zonasi sekolah Grade 1. Bahkan ada yang bermain curang dengan mencantumkan alamat kakek atau paman dalam formulir pendaftaran supaya mendapat jatah tempat di sekolah yang diinginkan dengan risiko ditolak jika ketahuan. Namun jika sudah terlanjur diterima maka sekolah tidak berhak mengeluarkan siswanya.
Makanya, di Inggris harga rumah juga dipengaruhi oleh tingkat sekolah di area tersebut. Semakin dekat dengan sekolah favorit, harga rumah makin mahal, dan tambah susah mencari rumah kosong yang bisa disewa.
Di Inggris, sudah menjadi kebiasaan umum jika ada keluarga berpindah-pindah karena alasan sekolah si anak.
Meski persaingan masuk sekolah Grade 1 bisa membuat orang geleng-geleng kepala, pendidikan dasar di Inggris bebas pungutan. Semua anak dijamin mendapatkan sekolah. Tak akan ada cerita anak terpaksa masuk sekolah swasta dan harus membayar mahal. Kalaulah masuk sekolah swasta adalah karena orangtua yang menghendaki.
Jaminan pendidikan dasar ini dikuatkan dengan Undang Undang yang menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap anak. Justru orangtualah yang akan dikenai sanksi jika terbukti nyata menelantarkan pendidikan anaknya.
Adapun bagi anak-anak dengan kecerdasan di atas rata-rata, di London dan sekitarnya ada sekolah setingkat SMP/SMA yang disebut “Grammar School” atau sekolah unggulan tanpa biaya sepeser pun alias gratis.
"Grammar School" berisi anak-anak yang lulus “11+ exam”. Ada jatah zonasi (asalkan lulus tes) dan ada juga yang berhak masuk tanpa zonasi (dibutuhkan nilai yang lebih tinggi dari nilai zonasi).
Jumlah sekolah unggulan ini tak banyak. Sekitar 163 di seluruh Inggris bagian selatan. Rumor yang beredar menyebutkan jebolan "Grammar School" banyak yang melanjutkan ke Univeritas ternama seperti Oxford dan Cambridge.

Ilustrasi. (Photo by Nathan Dumlao on Unsplash)
Zonasi di IndonesiaSistem zonasi Pendidikan di Indonesia ini awalnya diniatkan untuk menyamaratakan hak pendidikan.
"Kewajiban pemerintah dan sekolah adalah memastikan semua anak mendapat pendidikan dengan memerhatikan anak harus masuk ke sekolah terdekat dari rumahnya," ujar Menteri Muhadjir dalam sebuah pernyataan pada Rabu (19/6/2019).
"Karena pada dasarnya anak bangsa memiliki hak yang sama. Karena itu, tidak boleh ada diskriminasi, hak eksklusif, kompetisi yang berlebihan untuk mendapatkan layanan pemerintah. Sekolah negeri itu memproduksi layanan publik. Cirinya harus ‘non-excludable’, ‘non-rivarly’, dan ‘non-discrimination’," lanjutnya.
Idenya bagus, namun penerapan sistem ini harus melalui banyak pertimbangan karena sistem yang sama belum tentu berhasil atau cocok diterapkan di wilayah yang berbeda.
Apakah jika kebijakan ini berhasil diterapkan di negara maju seperti Inggris berarti akan suskes juga untuk Indonesia? Belum tentu!
Masalah yang sebenarnya harus lebih diperhatikan adalah filosofi yang mendasari sistem pendidikan itu sendiri. Apa sebenarnya yang ingin disamaratakan? Apakah kemampuan akademis? Kemampuan berfikir kritis? Pembentukan karakter berideologis? Menjadikan peserta didik berwawasan luas? Menjadikan anak didik beriman dan tidak selalu mendewakan budaya barat?
Bisakah sebenarnya sistem pendidikan yang ada sekarang memproduksi anak didik yang demikian?
Kalaulah memang ingin menyamaratakan pendidikan, sudahkah ada pemerataan sarana dan prasarana belajar? Sudahkah ada pemerataan guru-guru yang mumpuni dan berkualitas? Adakah juga keseimbangan antara jumlah siswa didik dan ketersediaan sekolah?
Mengubah kebijakan yang sudah berpuluh-puluh tahun diterapkan memang tak mudah. Apalagi jika tujuan bersekolah dan kegiatan pendidikan masih belum di rombak. Apakah masyarakat kita beranggapan jika sekolah adalah demi mendapat pekerjaan bagus di masa depan, atau untuk membentuk kepribadian generasi bangsa? Apakah sekolah demi status sosial atau menaikkan kemampuan intelektual? Apakah sekolah karena itulah jenjang kehidupan yang berikutnya, atau karena kecintaan pada ilmu yang bermanfaat untuk banyak orang?
Ada kesan kebijakan zonasi ini terburu-buru (tanpa ‘research’ yang mendalam dan evaluasi), sementara tidak ada upaya (atau sangat kecil) untuk mengangkat sekolah-sekolah yang masih jauh dari standar kelayakan menjadi sekolah yang pantas menjadi tempat lahirnya generasi emas Indonesia.
Sayangnya, hal-hal krusial tentang dasar-dasar dan tujuan pendidikan serta aktor dan faktor utama yang menyukseskan pendidikan malah luput dari perhatian pemerintah.
Penulis: Yumna Umm Nusaybah (Pemerhati pendidikan dan masalah sosial, tinggal di London, Inggris)